Oleh: Makin Perdana Kusuma, Depok, 9 Juni 2025
Dalam hiruk pikuk kehidupan modern, gemuruh peradaban yang serba tergesa-gesa dan serba diukur dengan angka, di tengah deru tuntutan tanpa henti dari sistem ekonomi dan industri, di antara ceceran darah pertarungan dengan sesama pemanjat tangga karir dan sesama pelaku ekonomi, perlahan namun pasti muncul bisikan kerinduan yang mendalam di dalam diri manusia. Manusia rindu pada dirinya sendiri, diri yang tergilas oleh laju peradaban, diri yang termakan oleh gelegak nafsu pencapaian dan pengakuan, diri yang tenggelam, hanyut dan hilang dalam arus proses ekonomi. Manusia merasa “lelah menjadi mesin ekonomi”, terus-menerus dituntut untuk produktif, efisien, dan berkontribusi pada roda kapital. Selama beberapa dekade, narasi kesuksesan sering kali diukur melalui pencapaian materi, karir yang menanjak, dan kontribusi ekonomi yang besar.
Namun, di balik semua itu, tumbuh kesadaran bahwa ada sesuatu yang hilang, yang kemudian memantik “keinginan untuk kembali menjadi manusia lagi”, agar tak lagi sekedar menjadi faktor produksi.
Kondisi ini diperparah oleh perkembangan teknologi dan otomatisasi yang, alih-alih membebaskan manusia dari kerja keras, justru menciptakan tekanan baru. “Intensifikasi kerja” dan ekspektasi untuk selalu terhubung melalui perangkat digital telah mengaburkan batas antara kehidupan profesional dan personal (Hochschild, 1997).
Manusia modern sering kali merasa terjebak dalam siklus yang tak berujung, terus mengejar target dan tenggat waktu, hingga mengorbankan aspek-aspek penting lain dalam kehidupan, seperti hubungan sosial yang bermakna, waktu untuk refleksi diri, dan pengembangan potensi manusia secara holistik (Sennett, 2012).
Kerinduan ini mencerminkan kebutuhan mendasar manusia akan “kemandirian, pengembangan potensi, dan keterhubungan” (Ryan & Deci, 2000).
Sistem ekonomi dan industri yang terlalu berfokus pada eksternalisasi motivasi melalui insentif finansial sering kali mengabaikan kebutuhan psikologis intrinsik ini. Akibatnya, meskipun secara materi tercukupi, banyak individu merasa “terasing dan tidak menemukan makna” dalam pekerjaan dan kehidupan mereka (Frankl, 1946).
Muncul kesadaran bahwa “kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada akumulasi kekayaan materi”, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan psikologis dan spiritual yang lebih dalam (Seligman, 2002). Seperti yang disampaikan oleh biksu Zen
Haemin Sunim (2017) dalam bukunya, “kita terlalu sibuk berlari mengejar sesuatu di luar diri kita sehingga kita lupa akan keindahan dan kedamaian yang ada di dalam diri. Ketika kita ‘melambat’, kita mulai bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat.” Ini menggarisbawahi bahwa “ketenangan dan kebahagiaan sering kali ditemukan bukan dalam pencapaian eksternal, melainkan dalam kesadaran internal dan apresiasi momen saat ini”.
Tanda-tanda kerinduan ini semakin nyata dalam berbagai fenomena sosial, seperti meningkatnya minat pada spiritualitas, praktik mindfulness dan meditasi, gerakan slow living, dan pencarian akan pekerjaan yang lebih bermakna dan selaras dengan nilai-nilai pribadi.
Semakin banyak orang yang mempertanyakan model kesuksesan konvensional dan mencari cara untuk “mengintegrasikan kembali pekerjaan dengan kehidupan pribadi” serta menemukan keseimbangan yang lebih sehat (Crittenden, 2001).
Ada keinginan untuk menghargai waktu luang, membangun hubungan yang lebih dalam, mengeksplorasi kreativitas, dan berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang lebih berarti, “tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan kualitas pengalaman” (Haemin Sunim, 2017).
Kerinduan untuk kembali menjadi manusia seutuhnya ini bukanlah penolakan terhadap kemajuan ekonomi atau teknologi, melainkan sebuah seruan untuk re-evaluasi prioritas dan nilai-nilai kita sebagai manusia. Ini adalah panggilan untuk menciptakan ekosistem yang lebih manusiawi, yang mengakui dan menghargai kompleksitas kebutuhan manusia, yang tidak sekedar menjadi “mesin ekonomi” belaka. Dengan memberikan ruang bagi kemandirian, kreativitas, hubungan sosial, makna, serta melalui praktik kebajikan, praktik spiritual-keagamaan, yang dapat mengembalikan ketenangan batin dan keterhubungan dengan diri sejati (Pargament et al., 2013; Goleman & Davidson, 2017),
Kita dapat membangun masyarakat yang tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga kaya hati, berlimpah kebahagiaan dan kesejahteraan sejati. Sebab, hidup bukan hanya tentang mengumpulkan lebih banyak dengan cara yang lebih cepat, tapi lebih dari itu, menjadi manusia yang lebih hadir sepenuhnya di setiap momen kehidupan, lebih utuh dan lebih penuh.
Referensi:
Crittenden, A. (2001). The price of motherhood: Why the most important job in the world is still the least valued. Metropolitan1 Books.
Frankl, V. E. (1946). Man's search for meaning. Beacon Press.
Goleman, D., & Davidson, R. J. (2017). Altered Traits: Science Reveals How Meditation Transforms Your Mind, Brain, and Body. Avery.
Haemin Sunim. (2017). The things you can see only when you slow down: How to be calm in a busy world. Penguin Books.
Hochschild, A. R. (1997). The time bind: When work becomes home and home becomes work. Metropolitan Books.
Pargament, K. I., Koenig, H. G., & Perez, L. M. (2013). The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal of Clinical Psychology, 69(12), 1279–1296.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.
Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press.
Sennett, R. (2012). Together: The rituals, pleasures and politics of cooperation. Yale University Press.
Editor : Nofis


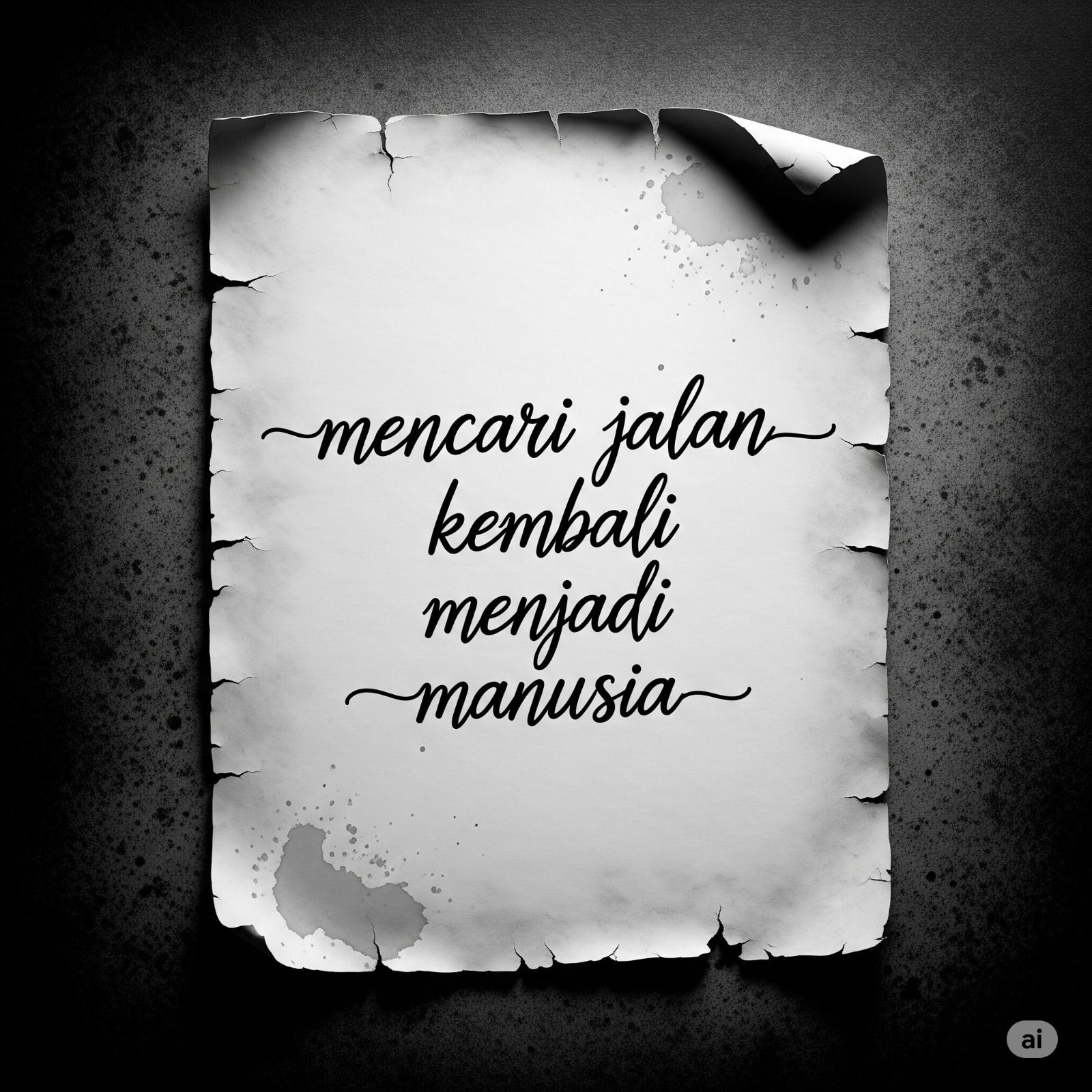





Social Header