Oleh: Prof Makin Perdana Kusuma - 6 Juli 2025.
Di dalam diri setiap manusia terdapat ruang sunyi yang tak tersentuh oleh hukum. Di sanalah ruh bersemayam—hening, tak terikat, tak tersentuh oleh logika legalistik. Hukum, betapapun agungnya, hanya mampu menjangkau tubuh yang bergerak, pikiran yang bernalar, dan perasaan yang bergetar. Hukum adalah jaring-jaring duniawi yang menata keteraturan, bukan cahaya yang menuntun ruh menuju asalnya. Seperti kata Al-Attas, “hukum agama adalah instrumen sosial, bukan wahana spiritual” (Al-Attas, 1995). Maka, ketika ruh bicara, hukum diam.
Hukum mengatur dimensi fisik karena tubuh adalah entitas yang tampak, dapat diukur, dan dapat dikendalikan. “Hukum positif lahir dari kebutuhan manusia untuk menata perilaku fisik dalam ruang sosial” (Soekanto, 2020). Oleh karena itu, hukum pidana, perdata, hingga hukum tata negara semuanya berakar pada tindakan-tindakan yang dapat diamati secara empiris. Tubuh yang mengejar kenikmatan badani, tubuh yang mencuri, tubuh yang menyerang, tubuh yang melanggar lalu lintas—semuanya tunduk pada hukum karena tubuh adalah wilayah yang bisa dibatasi.
Namun hukum tidak hanya berhenti pada tubuh. Ia merambah ke wilayah pikiran—melalui niat, motif, dan kesengajaan. Dalam hukum pidana, misalnya, “unsur mens rea (niat jahat) menjadi syarat penting dalam menentukan kesalahan” (Marzuki, 2021). Pikiran menjadi dimensi tak kasat mata yang tetap bisa diadili karena ia meninggalkan jejak dalam tindakan. Maka, hukum pun belajar membaca pikiran, meski dengan keterbatasan. Ia menafsirkan niat dari rangkaian peristiwa, dari bukti, dari logika. Sebab pikiran lah yang menggerakkan badan untuk mengejar kenikmatan badani, pikiran yang menggerakkan badan untuk mencuri, menyerang, melanggar lalu lintas dll.
Lebih jauh, hukum juga menyentuh perasaan. Dalam hukum keluarga, misalnya, “perasaan cinta, kasih sayang, dan empati menjadi dasar pertimbangan dalam hak asuh anak dan perceraian” (Nugroho, 2022). Hukum juga mencoba memahami luka batin, perasaan terhina, perasaan direndahkan, perasaan dipermalukan, trauma, rasa dirugikan dan rasa kehilangan, meski tak pernah bisa mengukurnya secara presisi. Ia mengatur perasaan bukan karena mampu menguasainya, tetapi karena perasaan itu berdampak pada tatanan sosial.
Namun ruh—ia berada di luar jangkauan hukum. Ruh tidak membutuhkan hukum, karena ia tidak bergerak dalam ruang empiris. Ruh tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mencintai dalam pengertian duniawi. “Ruh adalah substansi metafisik yang tidak tunduk pada hukum sebab-akibat duniawi” (Nasr, 2010). Hukum (aturan/syariat) di dalam agama pun pada dasarnya juga mengatur (“merekayasa”) aktifitas/fenomena badaniah, pikiran dan perasaan dan interaksi antar dimensi dan antar manusia secara badaniah, pikiran dan perasaan, agar badan, pikiran dan perasaan setiap unit manusia pemeluk agama tersebut mencapai/mendapatkan keadaan yang baik, aman, tenang dan damai. Yang disebut dengan berkah dan musibah pun sebenarnya adalah persepsi oleh badan, pikiran dan perasaan. Sementara ruh melampaui dimensi badan, pikiran dan perasaan. Maka, ruh tidak diatur oleh hukum/aturan, karena ia adalah Cahaya yang mengatur Dirinya sendiri. Seperti kata Al-Attas (1995) di awal, “hukum agama adalah instrumen sosial, bukan wahana spiritual”.
Kesimpulannya, hukum adalah instrumen duniawi yang mengelola keteraturan fisik, pikiran, dan perasaan manusia dalam masyarakat. Ia dibutuhkan untuk menjaga harmoni sosial, tetapi tidak relevan untuk mengatur dimensi ruhani yang bersifat transenden. Ruh tidak membutuhkan hukum karena ia tidak hidup dalam ruang sosial, melainkan dalam ruang kesadaran yang tak terdefinisikan.
Namun justru di situlah letak keindahan dan keterbatasan hukum. Ia agung dalam keteraturannya, tetapi takluk di hadapan keheningan ruh. Maka, manusia yang hanya hidup dalam hukum akan kehilangan kedalaman. Ia akan menjadi mesin yang taat, tetapi kosong. Sebaliknya, manusia yang menyadari bahwa ruhnya tak diatur hukum akan berjalan dengan kesadaran yang lebih tinggi—bukan karena takut dihukum, tetapi karena tahu siapa Dirinya.
Referensi:
• Al-Attas, S. M. N. (1995). Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam. ISTAC.
• Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana.
• Nasr, S. H. (2010). The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, Islam's Mystical Tradition. HarperOne.
• Nugroho, R. (2022). Hukum Keluarga dalam Perspektif Sosial dan Emosional. Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14(2), 112–129.
• Soekanto, S. (2020). Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat Indonesia. Rajawali Pers.
_____________________________________________________
"MPK’s Literature-based Perspectives"
Turning Information into Knowledge – Shaping Knowledge into Insight
Editor : Nofis Husin Allahdji


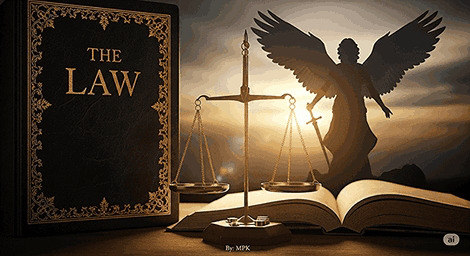




Social Header